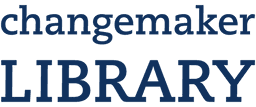Changemaker Library uses cookies to provide enhanced features, and analyze performance. By clicking "Accept", you agree to setting these cookies as outlined in the Cookie Policy. Clicking "Decline" may cause parts of this site to not function as expected.
Mohammad AlhabsyiIndonesia • Malaria Center
Ashoka Fellow sejak 2012
Ashoka Fellow sejak 2012
Meskipun beberapa dekade upaya pengendalian malaria di Indonesia difokuskan secara eksklusif pada pengobatan kuratif, Dr. Mohammad Alhabsyi telah mengubah praktik pemberantasan malaria menjadi pendekatan kolaboratif dan preventif di seluruh lembaga pemerintah dan sektor komunitas lokal.
Orang
Dr. Moh lahir dan besar di kota Ambon, Maluku sebagai anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ayahnya, meski berasal dari Ambon, lahir dan besar di Jawa. Ketika ayahnya bergabung dengan militer, mereka menugaskannya ke sebuah stasiun di Ambon, di mana dia bertemu dengan ibu Dr. Moh dan mereka membesarkan keluarga. Setelah pensiun dari kuliah di Universitas Pattimura, ayahnya kembali ke Jawa. Dr. Moh diajari empati dan nilai-nilai sosial dari ayahnya, yang berusaha untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung terlepas dari seberapa sedikit keluarganya sendiri. Ketika Dr. Moh masih di sekolah dasar, dia bermimpi menjadi seorang dokter, ingin membantu orang sebanyak mungkin. Ketika kakeknya sakit, dia harus menempuh perjalanan empat jam untuk mencari dokter. Pengalaman ini menggerakkan dia untuk menciptakan peluang bagi semua orang untuk menjadi sehat. Dia belajar ketekunan dan dedikasi dari ayahnya, yang memberinya dukungan penuh saat dia mendaftar di sekolah kedokteran. Selama kuliah, Dr. Moh belajar dari masyarakat setempat; merasakan besarnya bagaimana orang menderita masalah kesehatan. Setiap musim liburan di sekolah dia mengatur teman-teman sekolah kedokterannya untuk pergi ke daerah terpencil untuk melayani masyarakat. Sikapnya yang tidak memihak membuatnya disambut baik oleh organisasi santri dan ormas Islam lainnya. Setelah lulus, Dr. Moh menjadi kepala pos kesehatan kecamatan di Kepulauan Sula — sebuah kabupaten terpencil di mana dia menjadi satu-satunya dokter. Dia menghadapi lingkungan yang dipolitisasi dan memilih untuk tidak bersekutu dengan satu kelompok politik, melainkan membentuk koneksi yang luas. Dari bekerja di dalam masyarakat, ia menemukan bahwa selain kebutuhan akan akses yang sama ke fasilitas perawatan kesehatan, masyarakat juga perlu berperan dalam meningkatkan kesehatannya sendiri. Ia kemudian ditugaskan sebagai pegawai negeri di departemen Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Provinsi. Selama di sana, wabah Malaria yang sangat besar terjadi pada tahun 2003. Di satu daerah, enam puluh orang meninggal dalam enam hari. Tiba-tiba dr Moh menyadari bahwa wabah ini bukan hanya masalah kesehatan. Dia bertekad untuk mengakhiri mentalitas pemerintah "bukan departemen saya". Dari dalam, ia mulai mengubah budaya birokrasi. Dr. Moh dan rekan-rekannya berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Mengetahui wabah tersebut merupakan puncak dari permasalahan yang sudah berlangsung lama baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah, Dr. Moh melakukan terobosan penting dengan mendirikan Malaria Center. Proses demokrasi yang dia terapkan di tingkat komunitas bermula dari masa kecilnya: ayahnya selalu membiarkan dia memutuskan dan mengejar mimpinya. Untuk lebih mengembangkan dan menyebarkan idenya, Dr. Moh telah mengambil cuti selama lima tahun dari tugasnya di dinas kesehatan.
Ide Baru
Pada tahun 2003, wabah malaria melanda banyak desa di Halmahera Selatan, Indonesia yang memakan korban 267 jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, Dr. Moh menyadari bahwa pemberantasan penyakit malaria dan penyakit menular adalah tanggung jawab setiap orang. Melalui Malaria Center, ia mengembangkan sistem terintegrasi yang menghubungkan masyarakat dan berbagai kantor pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengobatan malaria. Dia telah mengubah cara pemerintah menangani pengendalian malaria dengan membalik strategi dari atas ke bawah ke bawah ke atas. Strateginya dimulai dengan individu dan lingkungan, dan pengobatannya sekarang membuat anggota masyarakat memimpin pengendalian penyakit yang dibawa nyamuk dan melibatkan kantor pemerintah untuk mengambil bagian dalam upaya tersebut. Melalui proses baru ini, Dr. Moh menciptakan peran baru bagi individu di desa, memberdayakan mereka dengan alat dan metode untuk mengidentifikasi potensi wabah penyakit dan memulai pencegahan di tingkat hiper-lokal. Dr. Moh mengembangkan Komite Malaria Desa, sebuah sistem yang mendidik anggota masyarakat tidak hanya tentang apa yang menyebabkan malaria dan bagaimana penularannya, tetapi bagaimana mengenali tanda dan gejala, meningkatkan praktik kolektif pencegahan dan menanamkan perilaku mencari pengobatan. Dia juga membuat saluran untuk menghubungkan kebutuhan lokal dengan kantor pemerintah yang sesuai, yang telah berhasil mencegah wabah selama tiga tahun terakhir, terutama untuk populasi yang rentan, seperti bayi dan ibu hamil. Dr. Moh dan rekan-rekannya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengeluarkan peraturan yang memaksa institusi pemerintah utama untuk bekerja sama dalam pemberantasan malaria. Melalui pengembangan kurikulum untuk siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar, Dr. Moh mendidik generasi muda Indonesia tentang malaria. Dia juga telah melobi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa 40 persen anggaran desa tahunan dialokasikan untuk pemberantasan malaria di tingkat daerah. Hingga saat ini, Malaria Center telah berdiri di tujuh kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Saat ini, Dr. Moh dan rekan-rekannya sedang mengerjakan replikasi metodenya di pulau-pulau di Indonesia Timur, di mana provinsi Sulawesi Selatan dan Barat sudah memulai model tersebut. Kementerian Kesehatan dan Global Fund telah mereplikasi model tersebut di delapan dan lima provinsi, masing-masing.
Masalah
Malaria tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di daerah tropis dan subtropis di dunia. Hampir setengah dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis malaria, dengan provinsi di Timur memiliki insiden penyakit tertinggi. Terlepas dari upaya pengendalian malaria selama puluhan tahun oleh pemerintah, laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2009 menemukan lebih dari 500.000 kematian akibat penyakit tersebut (dengan perkiraan 900 orang meninggal per 100.000 kasus). Menurut laporan yang sama, 90 persen dari kematian tersebut adalah anak-anak. Untuk anak-anak yang selamat dari episode malaria berat, mereka menderita gangguan belajar dan kerusakan otak; episode berulang sering menyebabkan buruknya perkembangan fisik dan mental masa kanak-kanak. Para ibu dan anak yang belum lahir juga menghadapi risiko serius dari malaria. Di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, masyarakat kurang memiliki informasi dan pemahaman ilmiah tentang penyakit tersebut — mereka tidak tahu dari mana datangnya penyakit, tidak dapat mengenali tanda atau gejalanya dan tidak tahu bagaimana penularannya. penyakit itu terjadi. Selama ratusan tahun, populasi ini mengaitkan gejala malaria dengan mitos dan takhayul. Pasien beralih ke tabib tradisional untuk penjelasan dan pengobatan, tidak satupun yang benar atau mujarab. Karena kendala geografis yang mahal, yang mengakibatkan biaya transportasi tinggi, orang tidak berobat. Pusat kesehatan di desa-desa ini, jika ada, tidak memiliki kapasitas untuk merawat pasien dan kekurangan peralatan medis untuk melakukan tes darah untuk diagnosis. Hanya ada 30 pusat yang melayani populasi di 400 pulau di Kabupaten Halmahera Selatan saja. Kondisi tersebut membuat hampir tidak mungkin pemberantasan penyakit malaria di daerah-daerah tersebut. Sejak tahun 1950-an, intervensi pemerintah dalam pengendalian malaria menggunakan pendekatan kuratif, dengan fokus hanya pada pengobatan simtomatik dan bukan pada tindakan pencegahan. Terlepas dari upaya pemerintah, situs rawan malaria masih ada di seluruh lingkungan, terutama di daerah pesisir dan rawa, seperti Halmahera Selatan, yang merupakan tempat berkembang biak yang sempurna bagi nyamuk Anopheles. Pendekatan pemerintah dari atas ke bawah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan seperti sanitasi dan jalan tidak terkoordinasi dan menyisihkan masyarakat sehingga tidak efektif melawan malaria. Selain itu, kurangnya komunikasi dan pemantauan oleh kantor pemerintah (mis. Dinas Pekerjaan Umum dan Perikanan) mempersulit terciptanya solusi kesehatan yang komprehensif. Terakhir, kemiskinan sistemik dan dampak ekonomi lainnya merupakan konsekuensi serius dari malaria. Penyakit ini tidak hanya memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang, tetapi juga memperburuk sumber daya yang sudah terbatas.
Strateginya
Strategi Dr. Moh untuk memberantas malaria di pedesaan Indonesia Timur ada tiga: (i) mengkoordinasikan badan-badan pemerintah untuk menangani pencegahan malaria (ii) pengobatan (iii) bekerja dengan komunitas lokal untuk mendidik, mengakhiri stigma, dan takhayul. Ia melakukan ini dengan meningkatkan kesadaran akan penyebab malaria dan memberikan insentif, peralatan, dan pengetahuan untuk melengkapi layanan medis yang ada di pedesaan. Kunci dari strategi Dr. Moh adalah memahami cara mendapatkan dukungan dari pemerintah. Melalui Malaria Center, Dr. Moh mendidik pemerintah daerah tentang pendekatan terpadu untuk mengatasi malaria, terutama melalui kerja sama berbagai kantor pemerintah (Biro Perencanaan Kabupaten, Biro Pembangunan Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) , dikoordinasikan di bawah kantor walikota distrik. Identifikasi walikota sebagai "pemimpin" adalah strategi kunci. Walikota adalah politisi utama di setiap distrik. Pegawai negeri sipil di distriknya harus mengikuti arahannya. Ketika tingkat malaria turun drastis setelah implementasi Malaria Center, walikota menuai liputan media yang positif dan penghargaan atas keberhasilannya. Namun, program ini tidak terikat pada walikota tertentu, jadi ketika walikota baru terpilih masing-masing harus melanjutkan tradisi pusat yang diamanatkan pemerintah. Malaria Center mengatur bagaimana setiap kantor harus berkoordinasi dan merespon kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk meminimalisir tempat berkembang biak nyamuk, warga bekerja sama dengan dinas perikanan dan pertambangan untuk menggeser lubang tambang yang tidak terpakai, atau dengan dinas pertanian untuk mengubah sawah yang tidak terpakai menjadi tambak ikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Ketenagalistrikan akan menindaklanjuti usulan desa untuk melaksanakan proyek sanitasi dan jalan, termasuk perbaikan konstruksi drainase. Alternatifnya, untuk wilayah pesisir, Pekerjaan Umum akan membangun tanggul air untuk menahan air laut masuk dan bertahan setelah air pasang untuk mencegah penumpukan air yang tergenang, tempat berkembang biak nyamuk. Selain mengatasi tantangan dengan lingkungan alam, strategi Dr. Moh berfokus pada mendidik populasi yang paling rentan di daerah pedesaan. Karena anak-anak berisiko tertinggi terkena malaria, Dr. Moh menyalurkan Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah dasar di desa menjalankan kurikulum lokal tentang malaria. Dipimpin oleh Dr. Moh dan timnya, mereka mengembangkan kurikulum bersama petugas kesehatan, guru sekolah dasar, dosen universitas, dan UNICEF. Setelah melalui kurikulum, siswa kelas 2 sd 5 mampu mengidentifikasi jentik nyamuk malaria dan tempat perkembangbiakannya, serta memahami cara pemberantasan malaria. Yang terpenting, anak-anak membagikan tindakan pencegahan ini dengan orang tua mereka. Para orang tua yang bangga, terutama para ibu, menyebarkan berita ini kepada orang dewasa lainnya di masyarakat. Hingga saat ini, Dr. Moh telah memperkenalkan program tersebut di 250 sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Selatan. Strategi Dr. Moh juga mempertimbangkan komunitas pada umumnya. Dr. Moh memandu pembentukan Komite Malaria Desa untuk penanggulangan malaria berbasis komunitas. Sebelum membentuk panitia, Dr. Moh bertemu dengan para kepala desa untuk membahas strategi pencegahan wabah dan pengendalian penyebaran penyakit. Jika desa berminat, mereka mengirimkan dua orang wakil desa untuk mengikuti program pelatihan, serupa dengan pejuang Malaria Desa berbasis remaja, di mana mereka belajar tentang malaria, jenisnya, penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Dengan menggunakan latihan pemetaan tubuh manusia, penduduk desa mengidentifikasi tanda dan gejala di seluruh tubuh. Latihan pemetaan desa mengajarkan para perwakilan untuk mengidentifikasi tempat berkembang biak di desa mereka sendiri. Pelatihan juga mencakup observasi langsung ke lokasi perkembangbiakan dan larva yang diambil dari sampel air. Dengan temuan tersebut, warga desa yang dipimpin oleh panitia desa, termasuk bidan atau perawat desa, mencari cara untuk menghentikan siklus hidup jentik-jentik guna mengurangi penularan penyakit malaria. Kegiatan lainnya termasuk pembersihan genangan desa pada hari Jumat setiap minggu untuk mencegah terbentuknya tempat berkembang biak dan kampanye publik yang berfokus pada kesadaran malaria melalui pertandingan sepak bola. Jika tindakan pencegahan tidak dapat menahan wabah, penduduk desa dididik tentang berbagai pilihan layanan kesehatan dan cara terbaik untuk mencari perawatan medis. Selain menyebarkan model pembelajaran inovatif ke kabupaten dan provinsi lain, Dr. Moh saat ini menerapkan model ini untuk mengatasi penyebaran epidemi HIV / AIDS di wilayah tersebut. Cabang ketiga dari strategi Dr. Moh berfokus pada peningkatan layanan dan pengobatan medis yang ada untuk malaria dengan strategi, fasilitas, dan pengetahuan yang lebih baik. Salah satu tantangan yang berhasil dinavigasi oleh Dr. Moh adalah rendahnya tingkat partisipasi imunisasi di antara wanita hamil dan bayi di pedesaan. Strategi Dr. Moh mengintegrasikan pencegahan malaria ke dalam layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah ada di desa dengan menciptakan insentif bagi keluarga untuk memastikan anaknya mendapatkan imunisasi. Bekerja sama dengan UNICEF dan pos kesehatan desa, Dr. Moh memberikan kelambu insektisida gratis kepada ibu hamil yang menerima perawatan prenatal dan untuk anak balita dengan imunisasi primer lengkap. Deteksi malaria seringkali menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pusat kesehatan pedesaan. Dengan demikian, Pusat Malaria Dr. Moh membantu pusat kesehatan desa pedesaan dengan penyediaan tes diagnostik cepat. Untuk meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan di berbagai tingkatan, Dr. Moh memberikan pelatihan tentang prosedur operasi standar dan penggunaan mikroskop untuk tes darah malaria melalui Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui program magang, menetapkan empat puskesmas sebagai model bagi puskesmas lainnya; Puskesmas yang diperbaiki idealnya akan memberikan bantuan kepada pos-pos kesehatan desa. Akhirnya, Dr. Moh telah mengambil langkah-langkah untuk mengadvokasi penerapan strateginya, termasuk pendanaan untuk mengukur dan melembagakan metodenya. Strategi ini sesuai dengan perubahan anggaran baru-baru ini di Indonesia — desentralisasi anggaran ke daerah lokal dari pusat. Untuk mengamankan pendanaan dan menjamin keberlanjutan Malaria Center-nya, Dr. Moh menganjurkan adanya Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menetapkan bahwa 40 persen dari Alokasi Dana Desa tahunan harus mendanai proposal dari Panitia Malaria Desa. Malaria Center juga akan mengkoordinasikan pendanaan dari sumber lain, misalnya dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah PNP, APBD Mandiri dan APBD kabupaten. Hingga saat ini, enam belas lembaga pemerintah telah terlibat dan mendukung usulan tingkat desa untuk memberantas malaria. Pemprov juga berjanji setiap kabupaten harus memiliki Malaria Center. Selain itu, Dr. Moh memfasilitasi hubungan antara komite malaria desa dan layanan keuangan mikro untuk mendirikan koperasi dan menjalankan bisnis warung internet. Keuntungan tidak hanya menopang upaya desa, koneksi internet membantu membangun sistem informasi untuk Malaria Center.