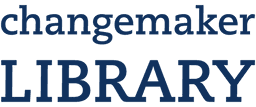Changemaker Library uses cookies to provide enhanced features, and analyze performance. By clicking "Accept", you agree to setting these cookies as outlined in the Cookie Policy. Clicking "Decline" may cause parts of this site to not function as expected.
John BalaIndonesia • Ashoka Fellow sejak 2003
John Bala adalah seorang ahli bantuan hukum Indonesia yang metodenya untuk mendamaikan tradisi lokal dengan hukum modern membantu masyarakat adat dan negara untuk menyepakati pembagian dan penggunaan tanah.
Orang
John diadopsi pada usia muda dan dibesarkan oleh seorang polisi dan istrinya. Selama masa kecilnya tinggal di kompleks keluarga polisi, John menyaksikan kekerasan dan ketidakadilan terhadap tahanan yang dilakukan oleh polisi, orang-orang yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan. Pengalaman-pengalaman awal ini, dan kesadaran akan ketidakadilan yang mereka ilhami, mengantarkan John untuk menempuh pendidikan hukum, yang ia lakukan, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Cendana (Kupang) pada tahun 1993. Seperti pada tahun-tahun awalnya di sekolah menengah dan sekolah menengah atas, dia adalah pemimpin di universitas, memimpin Senat Mahasiswa dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan hukum kepentingan umum. Setelah gempa bumi dahsyat di Flores pada tahun 1992, John mengorganisir sukarelawan mahasiswa untuk membantu masyarakat yang paling parah terkena dampak bencana. Dia bertahan dengan upaya itu selama dua tahun, karena dia tertarik pada rehabilitasi jangka panjang masyarakat, bukan pada upaya bantuan cepat yang hanya akan menghasilkan pemulihan sebagian. Setelah lulus, John ingin melihat situasi kecil, komunitas miskin di Flores, dan untuk memahami lebih lengkap spektrum dan fungsi dari upaya warga yang mendukung komunitas-komunitas ini. Dia kemudian mendaftar sebagai sukarelawan dengan organisasi warga yang besar dan terkenal di Flores, SANRES: Yayasan Kesejahteraan Flores. Latar belakangnya di bidang hukum membekalinya dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengawasi upaya advokasi Yayasan dan organisasi lain, INSIST di Yogyakarta. Kemudian, ia bekerja di wilayah pulau Pulau Babi, di mana ia melibatkan masyarakat dalam menilai kebutuhan mereka dan kemudian merancang cara proaktif untuk berhubungan dengan pemerintah dan industri. Pengalaman-pengalaman ini, dan perspektif yang ditimbulkannya, berkontribusi pada pendirian Lembaga Bantuan Hukum NTT John pada tahun 1998.
Ide Baru
John Bala telah menciptakan masyarakat bantuan hukum yang mengkhususkan diri dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Tidak ada pihak yang memiliki catatan ideal dalam menggunakan tanah, dengan korupsi dan penggunaan wewenang yang berlebihan di pihak negara dan diskriminasi dan konflik komunal di antara masyarakat. John telah menciptakan fungsi masyarakat sipil baru yang bekerja secara rinci dengan komunitas yang terlibat dalam konflik untuk menemukan dengan tepat di mana dan bagaimana konflik muncul dan kemudian memfasilitasi solusi yang diakui di tingkat kabupaten dan provinsi. Secara umum, sistem pengelolaan lahan tradisional mencadangkan area lahan yang berbeda untuk penggunaan yang berbeda—jenis pertanian yang berbeda, perburuan, penggunaan ritual, dan perlindungan lingkungan. Ketika sebuah perusahaan negara atau swasta masuk dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak atas tanah yang ingin digunakannya, ia mulai membuka dan mengolah tanpa pandang bulu. Tiba-tiba ia dihadapkan dengan warga yang marah, dan konflik—kadang dengan kekerasan yang brutal—sering terjadi. Dalam satu dekade kerja tingkat komunitas dengan orang-orang di Indonesia bagian timur, John mengetahui bahwa situasi eksplosif ini dapat dideteksi dan diredakan. John memperkenalkan sebuah proses di mana orang-orang memetakan praktik penggunaan lahan mereka dan kemudian mengusulkan kepada negara bagian di mana dan bagaimana mereka dapat berbagi. Sementara area yang ditandai untuk penggunaan ritual mungkin sangat terlarang untuk pengembangan, lahan yang dialokasikan untuk fungsi yang kurang kritis dapat ditawarkan dengan kompromi. Melalui proses ini, demokratisasi penguasaan tanah dimulai dengan dua cara. Pertama, masyarakat mulai mendokumentasikan sewa mereka untuk mengajukan kepemilikan tanah individu dan komunal. Ini adalah penyimpangan yang signifikan dari sistem yang berlaku di mana seorang kepala suku lokal saja yang diakui sebagai pemilik tanah. Ini adalah aktivitas yang berpotensi radikal dan mengganggu yang secara alami mengungkap ketidakadilan dalam sistem kepemilikan tanah tradisional. Misalnya, tradisi melarang perempuan memegang tanah, meskipun dalam praktiknya mereka menuai dan menabur untuk kelangsungan hidup mereka. John memperkenalkan kerangka hukum atau kuasi-hukum untuk menafsirkan praktik semacam itu. Sekarang masyarakat memiliki kepentingan dalam mempertimbangkan kembali tradisi semacam itu—apakah manfaat kolektif dari memformalkan hak perempuan atas tanah, dan dengan demikian mempertanggungjawabkan tanah dalam negosiasi, lebih besar daripada manfaat apa pun yang dirasakan dalam berpegang teguh pada tradisi. John telah membangun sistem ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pulau-pulau yang terbentang dari Flores hingga Timor. Dia sekarang berencana untuk memperkenalkan prinsip dan prosedurnya kepada organisasi mitra di seluruh Indonesia.
Masalah
Baik sistem sosial tradisional maupun modern menimbulkan hambatan bagi penggunaan lahan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat di Indonesia. Apa pun ketidakadilan pra-kolonial yang ada diperkuat oleh kebijakan Belanda dan Portugis dalam memilih dan menopang pemimpin lokal yang disukai. Ketika negara Indonesia terbentuk dan mulai mempengaruhi pulau-pulau yang lebih terpencil, kebijakan tersebut dipertahankan, tetapi dilengkapi dengan birokrasi negara dengan otoritas tertinggi atas semua masalah pertanahan. Kepentingan negara dan sektor swasta menentukan kebijakan penggunaan lahan selama tiga puluh tahun program pembangunan ekonomi rezim Orde Baru, menyerahkan tanah komunal kepada industri ekstraktif, perkebunan tanaman komersial, dan militer. Negara secara rutin mengambil alih tanah untuk tujuan ini. Hak-hak masyarakat adat dan lokal seringkali diabaikan karena beberapa masalah yang saling terkait: 1) meskipun peraturan daerah yang ada mengatur tata guna lahan dan ruang secara bijaksana, seringkali bersifat feodalistik; 2) tingkat pendidikan yang rendah dan tidak dapat diaksesnya catatan publik dan informasi lainnya bersekongkol melawan masyarakat, yang sering salah informasi oleh pejabat; 3) masyarakat belum terbiasa terlibat dalam organisasi modern, sehingga tidak memiliki daya tawar atau kemampuan berbicara; 4) masyarakat juga tidak membangun jaringan antara dirinya dengan orang lain yang mungkin lebih kompeten, seperti LSM atau universitas atau media. Lebih jauh lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak di antaranya cukup jauh dari yang lain, menyebabkan kesulitan komunikasi antar masyarakat dan berkontribusi pada kurangnya informasi. Berakhirnya era otoriter dan desentralisasi kekuasaan negara telah membangkitkan keprihatinan publik atas konflik tanah, di antara orang-orang yang direbut serta struktur masyarakat sipil yang mendukung mereka. Namun, secara umum, hanya ada sedikit inovasi seputar masalah pelik distribusi tanah. Beberapa, tetapi jelas tidak semua, kasus dapat diperjuangkan di pengadilan. Baik sistem hukum maupun gerakan bantuan hukum belum mampu menangani persoalan ini secara sistematis secara nasional. Di Jawa, para petani dan pendukungnya membuat beberapa kemajuan dalam negosiasi reklamasi lahan untuk menghindari konflik kekerasan. Situasi bagi masyarakat adat agak berbeda. Aktivisme lingkungan yang mendesak cenderung ke arah protes daripada negosiasi. Inisiatif yang menjanjikan membantu masyarakat dan Departemen Kehutanan, misalnya, mencapai kesepakatan konservasi di dalam dan sekitar taman nasional. Namun masalah umum—memperbarui hak atas tanah adat dengan cara yang efektif dan realistis—masih menuntut perhatian kreatif dari sektor sosial.
Strateginya
Konflik tanah tersebar luas, beragam dan seringkali rumit. Ketika John mulai membiasakan diri dengan berbagai konflik di provinsi asalnya, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dia menyadari bahwa tidak akan ada solusi tunggal. Ia ingin menciptakan layanan yang dapat bekerja pada dua level secara bersamaan, baik di dalam masyarakat maupun dalam dialog dengan sistem hukum dan birokrasi. Tidak akan cukup tanpa yang lain. Pengalaman John di provinsi telah mengajarinya bahwa masyarakat adat—diabaikan, dilecehkan, diperlakukan sebagai “orang lain” di tanah mereka sendiri—tidak terlalu menerima simpatisan luar yang terjun payung dengan solusi cepat. Hubungan jangka panjang diperlukan. Oleh karena itu John mulai membuat jaringan organisasi berbasis komunitas. Masing-masing dengan caranya sendiri akan menyentuh masalah tanah, menanggapi masalah dan konflik lokal. Beberapa adalah organisasi yang sudah ada, seperti koperasi petani, yang John bantu kembangkan dan arahkan ke metode yang lebih konstruktif dan tidak terlalu konfrontatif. Yang lainnya adalah organisasi baru yang digunakan John dan stafnya selama berbulan-bulan, melatih, membimbing, menunggangi gelombang kesuksesan dan kegagalan yang menyertai pendirian organisasi mana pun. Saat ini organisasinya, LBH-Nusa, yang didirikan pada tahun 1998, memiliki kelompok warga mitra di sepuluh dari lima belas kabupaten di NTT, yang terdiri dari puluhan kelompok masyarakat kecil dan menengah. Setelah menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, tim John memimpin pemetaan sosial partisipatif wilayah dan penelitian sosial. Hal ini membantu masyarakat untuk mengidentifikasi hukum adat setempat mengenai penggunaan lahan, seperti pengelolaan hutan, peraturan negara yang mengatur kegiatan perusahaan penebangan swasta, dan kebijakan negara untuk melestarikan keanekaragaman hayati kawasan konservasi. Pemetaan seringkali memberikan definisi yang lebih tepat tentang konflikJohn kemudian memfasilitasi para pemangku kepentingan di wilayah tersebut, termasuk perwakilan masyarakat setempat, perusahaan kayu swasta, dan pemerintah daerah untuk menemukan alternatif win-win solution dalam mengelola sumber daya. Pihak-pihak ini membuat kesepakatan dan John mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan proses penetapan kebijakan tingkat kabupaten yang baru. Dia dan rekan-rekannya telah menyusun kebijakan yang saat ini sedang dipelajari oleh legislatif daerah. “Simpul belajar” warga telah menjadi ide khas John untuk memberdayakan masyarakat sipil yang kuat, mengingat fakta bahwa sudah ada potensi lokal yang tersedia seperti organisasi berbasis masyarakat, pengetahuan adat untuk praktik konservasi alternatif, dan pengalaman bekerja dengan pembuat kebijakan. Di sepuluh kabupaten di NTT, John telah mengorganisir tujuh simpul semacam itu yang melibatkan total lima puluh empat kelompok masyarakat yang berbeda dan sebelas koalisi OMS. Setiap node telah membuat kemajuan sendiri sesuai dengan potensi lokal yang tersedia dan masalah yang dihadapi berbeda. Misalnya, ada simpul-simpul pembelajaran yang berfokus pada isu-isu seperti cara-cara non-kekerasan untuk reklamasi lahan perkebunan, pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal, pengembangan keterampilan pengorganisasian masyarakat yang efektif, dan lain-lain. Melalui jaringan simpul belajar John menyediakan saluran bagi semua komunitas untuk belajar satu sama lain. Tantangan John selanjutnya adalah membawa kesuksesannya di tingkat provinsi dan menerapkannya untuk dampak nasional. Ia melihat bahwa ide dan metodenya dapat meresap ke dalam organisasi mitra, tetapi lembaga bantuan hukumnya sendiri mungkin akan tetap fokus pada provinsi NTT. Penduduk asli dan masalah tanah mereka sangat beragam di seluruh negeri sehingga tidak realistis untuk mengharapkan bahwa John sendiri dapat mereproduksi seluruh proses pembelajaran—yang memakan waktu sepuluh tahun di satu provinsi—di tingkat nasional. Bagaimanapun, hari ini produk, teknik, dan keberhasilan sementaranya adalah alat untuk pengajaran. Dia sudah berpartisipasi dalam kelompok kerja nasional tentang masyarakat adat, yang memberinya akses ke organisasi mitra di seluruh negeri. Fakultas hukum di perguruan tinggi daerah terbukti menjadi mitra yang baik di NTT. Dia sekarang sedang mengerjakan manual yang akan memungkinkan mahasiswa hukum untuk memulai proyek serupa di tempat lain.